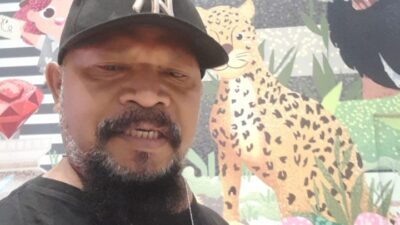Oleh: Syahrul Ramadhan
Epos Mahabharata karya Nyoman S. Pendit bukan hanya kisah kepahlawanan kuno, melainkan juga potret arketipe manusia yang terus berulang. Dalam Bab 14: Istana dari Papan Kayu, kita menemukan drama intrik kekuasaan yang sarat makna simbolis: sebuah istana indah yang ternyata dibangun dari bahan mudah terbakar, sebagai perangkap licik untuk menyingkirkan Pandawa. Dengan membaca kisah ini melalui lensa psikologi Carl Gustav Jung, kita bisa melihat bagaimana arketipe bayangan, pahlawan, orang bijak, hingga penipu masih hidup dan nyata dalam politik Indonesia masa kini.
Diceritakan bahwa:
“Duryodana dengan licik merancang istana yang seluruhnya terbuat dari kayu dan bahan mudah terbakar, dengan maksud membinasakan Pandawa bersama Kunti di dalamnya.” (Pendit, 2006: Bab 14)
Kutipan ini menyingkap arketipe Shadow atau bayangan, sisi gelap kepribadian yang penuh iri hati dan ambisi. Duryodana tidak mampu menerima keunggulan Pandawa, sehingga memilih jalan konspirasi. Dalam politik Indonesia, bayangan ini hadir dalam praktik oligarki, korupsi, dan politik uang: kekuasaan dipertahankan bukan lewat gagasan, melainkan manipulasi. “Istana kayu” adalah metafora bagi kekuasaan yang tampak megah di luar, tetapi rapuh karena dibangun di atas kepalsuan.
Namun, kisah ini juga memperlihatkan hadirnya Hero dalam diri Pandawa. Mereka tidak jatuh ke dalam perangkap, sebab mau mendengar suara kebijaksanaan. Pendit mencatat:
“Atas nasihat Widura, para Pandawa mengetahui tipu muslihat itu, sehingga mereka bersiap menyelamatkan diri.” (Pendit, 2006: Bab 14)
Pandawa mewakili arketipe pahlawan yang tidak hanya berani, tetapi juga bijak. Di sini tampak jelas bahwa keberanian tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan korban. Jika kita tarik ke Indonesia, rakyat bisa menjadi “pahlawan” politik bila kritis terhadap janji-janji manis dan tidak terjebak pada pencitraan. Namun, keberanian rakyat itu perlu ditopang oleh kebijaksanaan kolektif misalnya lewat suara akademisi, tokoh moral, atau masyarakat sipil yang jernih.
Figur Wise Old Man atau orang bijak hadir dalam diri Widura. Ia adalah penasihat yang jujur, meski tak selalu populer. Dalam konteks politik Indonesia, peran ini serupa dengan lembaga independen, media kritis, atau intelektual yang berani mengingatkan publik akan bahaya manipulasi. Suara mereka sering kali tidak nyaman bagi penguasa, namun justru menjadi penuntun agar masyarakat tidak masuk ke dalam jebakan “istana kayu” kekuasaan.
Di sisi lain, Trickster muncul dalam tokoh Purocana, arsitek yang membangun istana jebakan itu. Pendit menulis:
“Purocana, arsitek kepercayaan Kaurawa, membangun istana indah, tetapi seluruhnya dari papan dan damar yang mudah tersulut api.” (Pendit, 2006: Bab 14)
Trickster adalah pengelabuh, sosok yang lihai membungkus bahaya dengan keindahan. Dalam politik Indonesia, Trickster mewujud dalam para politisi oportunis atau buzzer digital: pandai menyusun narasi indah, membangun pencitraan, tetapi sesungguhnya menjerumuskan rakyat. Mereka adalah “arsitek istana kayu” masa kini memberi janji megah, tetapi menyembunyikan kerentanan.
Analisis Jung membuka mata bahwa drama Mahabharata bukan sekadar mitos India kuno, melainkan pola arketipe universal. Bayangan (Duryodana), Pahlawan (Pandawa), Orang Bijak (Widura), dan Penipu (Purocana) adalah wajah-wajah yang berulang dalam sejarah kekuasaan. Pertanyaannya: dalam politik Indonesia saat ini, siapa yang sedang membangun istana kayu? Siapa yang berperan sebagai pahlawan? Dan apakah suara bijak masih cukup kuat melawan bayangan serta tipuan?
Kisah Bab 14 memberikan sebuah pelajaran sederhana tetapi mendalam. Kekuasaan yang dibangun dengan tipu daya pada akhirnya akan runtuh, sebagaimana istana kayu yang mudah terbakar. Sebaliknya, keberanian yang ditempa dengan kebijaksanaan akan selalu menemukan jalan keluar. Jika rakyat mampu memainkan peran sebagai pahlawan, maka politik tidak lagi menjadi arena intrik, melainkan jalan menuju kemaslahatan. (*)